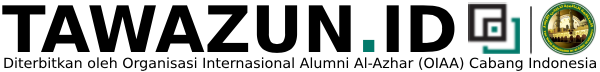Adagium “dapur, sumur, dan kasur” yang dikaitkan dengan perempuan barangkali sudah terlalu usang. Namun, tanpa menutup sebelah mata, bagi sebagian kalangan stigma dan justifikasi ini masih berlaku, setidaknya secara faktual meskipun bukan formal-eksplisit. Miris memang, tapi itulah realitanya. Lebih lanjut, di era modern ini perempuan masih seringkali diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek yang merdeka.
Paska kemerdekaan—lebih-lebih era reformasi, akses bagi perempuan terkait pendidikan, pekerjaan, informasi, keadilan, hak-hak politik dan lain sebagainya memang cenderung membaik, namun belum bisa dikatakan utuh. Secara lebih substansial, beberapa perempuan—atau bahkan sebagaian besar—masih kesulitan untuk memosisikan dan diposisikan setara dengan laki-laki. Tidak adil memang jika kita hanya mengambinghitamkan sistem sebagai faktor tunggal atas diskriminasi yang terjadi, pola pikir memiliki andil besar dalam membidani lahirnya situasi ini.
Dalam konteks umat Islam, hal ini tak jarang hadir dalam kerangka “langkah preventif yang syar’i” jika tidak ingin disebut pembatasan dan pengekangan. Pola pikir yang seolah mengasosiasikan perempuan dengan hukum Islam ini dapat dipastikan ada sebagai buah dari kejumudan dan kegagalan melihat Islam sebagai landasan hidup yang universal dan kontekstual; dinamis, ideal sesuai ruang dan waktu.
Contoh kecil dari kejumudan berpikir ini adalah betapa sering kita menyaksikan perdebatan-perdebatan fiqhiyyah seputar perempuan modern yang memilih berdikari, atau justifikasi kepada mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik dengan meragukan kompetensi, kapabilitas dan kredibilitasnya. Atau, betapa sering kita mendengar apologi yang menyatakan bahwa posisi-posisi strategis yang selama ini biasa diisi oleh laki-laki tidak bisa digantikan oleh perempuan dengan alasan bahwa mereka makhluk yang emosional, kurang mengedepankan akal dan logika.
Sikap yang cukup menarik bagi saya akhir-akhir ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Syekhul-Azhar, al-Imām al-Akbar Prof. Ahmad at-Thayyib dalam akun twitternya. Beliau menyampaikan bahwa sepanjang perempuan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai, ia berhak menduduki jawatan-jawatan publik—kenegaraan sekalipun, menjadi hakim dan berfatwa, tak ada bedanya dengan laki-laki.
Bagi sebagian kalangan, pernyataan ini kemungkinan besar akan dicap sebagai langkah pengkhianatan atas turāts dan khazanah hukum Islam yang dipahami dan diturunkan lintas generasi. Ya, sebagian dari Muslim memang masih memandang dan meyakini produk ijtihad dalam khazanah turāts sebagai sebuah dogma suci yang pantang direvisi. Ini berlaku bagi siapapun yang gagal paham atas konsep kontekstualisasi hukum sebagai keniscayaan. Jangankan merevisi hukum, mengompromikan pendapat dari selain mazhab yang diyakini pun terkadang masih diamini sebagi sesuatu yang tabu.

Langkah advokasi terhadap perempuan seperti yang dilakukan Syekhul-Azhar dan sarjana-sarjana Muslim lainnya patut diapresiasi. Sejatinya, langkah semacam ini tidak perlu juga dilabeli sebagai sesuatu yang progresif, melainkan keniscayaan yang memang selayaknya muncul dari setiap Muslim yang mau berpikir dan merenung, menyarikan asas dan kaidah fundamental agama sebagai terjemahan atas dinamisnya ruang dan waktu.
Pada akhirnya kita harus mengambil sikap, apakah kita memilih gerbong kejumudan dengan membatasi ruang gerak perempuan, ataukah kita memilih gerbong kontekstual; mengadvokasi perempuan dan memberdayakan mereka sesuai kapasitasnya untuk memakmurkan peradaban manusia dan agama Tuhan? Anda yang menentukan.
Baca juga artikel menarik di rubrik ISLAMUNA atau tulisan lain Azuma Muhammad