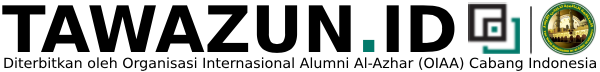Belum lama ini viral tentang kisah seorang perempuan bernama Aprila Majid yang berjuang mati-matian untuk menemukan suaminya yang bernama Muchamad Zhacky yang telah cukup lama hilang tak tentu rimbanya. Sambil membesarkan dua anaknya dan terus membesarkan harapan agar suaminya segera bisa ditemukan, akhirnya setelah setahunan mencari, ia mendapat titik terang jika suaminya masih hidup. Ternyata suaminya diketemukan ada di Palembang. Sebuah kabar gembira dan melegakan bagi ia dan kedua anaknya; Zidan beserta Alana. Namun, ada fakta mencengangkan yang membersamai informasi keberadaan suaminya, bahwa ternyata suaminya itu sengaja menghilang dan telah mempunyai pasangan baru.
Kasus serupa semacam itu ternyata cukup banyak terjadi di negeri Indonesia. Lantas, jika ditilik dari perspektif Islam, bagaimana hukumnya istri yang ditinggal suami selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun seperti kasus yang dialami Aprila di atas? Untuk tahu jawabannya, mari simak tulisan ini hingga akhir.
Dalam Islam, suami yang pergi hingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama secara fikih diistilahkan mafqûd. Entah hilangnya disebabkan pergi tanpa kabar, atau karena menjadi korban bencana alam, semisal banjir yang tanpa ditemukan jasadnya atau kabar keberadaannya. Dalam kondisi seperti itu, terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Pertama, si perempuan harus menunggu kejelasan status dirinya sampai diyakini bahwa ikatan pernikahannya dengan si suami telah terputus. Baik itu karena adanya kepastian kematian suaminya atau karena kabar talak untuknya dari si suami yang diketemukan kabarnya. Baru setelah itu, ia menjalani masa iddahnya. Kenapa begitu, karena dalam hal ini hukum asal statusnya adalah si suami masih hidup dan status pernikahan mereka masih berlaku secara menyakinkan sehingga tidak dapat dianggap batal kecuali harus secara meyakinkan pula.
Demikian pendapat Imam As-Syafi’i rahimahullâh dalam qaul jadîd.
Artinya: “Suami yang menghilang (karena pergi atau sebab lain) dan terputus beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini (yakni diduga kuat berdasarkan bukti, seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum), kabar kematian atau adanya talak, atau alasan sesamanya, seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian si istri menjalani iddah. Kenapa demikian, sebab, hukum asalnya adalah si suami masih hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin, sehingga hal ini tidak bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan dengannya,” (Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtâj pada Hawâsyais Syarwani wal ‘Abbâdi, [Beirut, Dârul Kutub Al-‘Ilmiyah: 1996], cetakan pertama, Jilid X, halaman 456)
Kedua, si perempuan harus menunggu sampai lewat masa empat tahun Qamariyah, kemudian melakukan idah selama empat bulan 10 hari. Masa empat tahun ini adalah standar karena merupakan batas maksimal usia kehamilan. Sedangkan perhitungannya dimulai sejak hilangnya keberadaan suami atau berdasar keputusan hukum dari hakim atas kematian suami.
Artinya: “Menurut kaul Qadîm, ia harus menunggu selama empat tahun, menurut satu versi: empat tahun itu dihitung sejak hilangnya si suami. Sementara menurut versi al-ashhah, dihitung sejak ada keputusan dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak di hitung. Kemudian ia menjalani idah perempuan yang ditinggal mati suaminya, baru nanti boleh menikah setelahnya. Ketentuannya demikian karena mengikuti putusan hukum Umar RA dalam kasus tersebut. Penggunaan acuan empat tahun, mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan.” (Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtâj, cetakan pertama, Jilid X, halaman 457).
Rasulullah
Kumpulan tulisan dengan spirit kecintaan kepada Rasulullah SAW dapat teman-teman temukan
di siniAdapun terkait hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan selama si suami menghilang tak tentu rimbanya, berikut ini ketentuannya. sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu j. IX, h. 6832:
Artinya: “Bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi, berupa mahar dan nafkah beserta hak-hak yang bersifat non materi, seperti memperbagusi dalam hal menggauli dan dalam hal hubungan yang baik serta berlaku adil.”
Ketika kemudian seorang suami ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban pemberian nafkah, tapi selagi istrinya rela dan lapang dada untuk saling berbagi, maka ikatan pernikahan tetap bisa dipertahankan. Hal ini tercermin dalam Al-Quran Surah Ath-Thalaq ayat 7:
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
Sebaliknya, tatkala si istri merasa tidak bisa bersabar akan hal tersebut, maka ia pun boleh menuntut hak tersebut kepada suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam kitab Al-Umm, juz VII, hal. 121:
Artinya: “Imam Asy-Syafi’i berkata, baik Al-Quran maupun Sunah telah menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah mencukupi kebutuhannya. Maka konsekuensinya adalah suami tidak boleh hanya sekadar berhubungan badan dengan istri tetapi kemudian menolak memberikan haknya, dan suami tidak boleh meninggalkannya sehingga kemudian istri diambil oleh orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jika ternyata demikian (tidak memenuhi hak istri), maka isteri boleh memilih antara tetap bersamanya atau pisah dengannya,”
Ketentuan di atas berlaku untuk nafkah secara umum. Baik itu nafkah lahir, maupun nafkah batin. Nah, pembahasan berikutnya ialah terkait soal durasi. Berapa lama-kah seorang suami boleh tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya? Terkait hal itu, ada perbedaan pendapat ulama. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya satu kali satu bulan. Pendapat ini berdasarkan pada ayat:
Artinya: “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”
Imam Ibnu Hazm berpendapat demikian, karena beliau memahami bahwa biasanya siklus haid perempuan adalah sebulan sekali, sementara perintah untuk menggauli istri pada ayat di atas menurut Ibnu Hazm adalah perintah yang menunjukkan kewajiban. Akan tetapi ulama lain tidak menganggap perintah di atas sebagai sebuah kewajiban. Sebagaimana Imam Asy-Syafi’i, beliau berpendapat bahwa batas waktunya ialah 4 bulan. Pendapat tersebut berdasarkan ketetapan yang dibuat Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khaththab. Pada masa itu, banyak lelaki yang pergi berperang meninggalkan istri mereka. Banyak sekali istri yang merasa sedih akan hal tersebut. Sesudah berdiskusi dengan Sayidah Hafshah, Umar kemudian memutuskan bahwa prajurit yang sudah bertugas selama 4 bulan di medan perang, ia harus pulang untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atau menceraikannya. Ketentuan ini termuat dalam Al-Umm, juz VII, hal. 121:
Artinya: “Umar bin Al-Khattab RA pernah menulis surat kepada para panglima perang mengenai para suami yang jauh istrinya, (dalam surat itu) beliau menginstruksikan kepada mereka agar mengultimatum para suami dengan dua opsi; antara memberikan nafkah kepada para istri atau menceraikannya. Kemudian apabila para suami itu memilih menceraikan para istri, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan selama meninggalkannya. Hal ini mirip dengan apa yang telah saya (Imam Asy-Syafi’i) kemukakan.”
Walhasil, berdasar beberapa pendapat ulama di atas, maka batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan; jika mengacu pendapat Imam Ibnu Hazm, sedangkan jika mengacu ketetapan Sayidina Umar bin Al-Khaththab sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syafi’i, maka batas maksimal suami tidak menafkahi istrinya adalah 4 bulan.
Tetapi yang menarik, terkhusus bagi kita yang tinggal di Indonesia, terdapat shighat ta’liq talak yang biasanya dibaca mempelai pria dan tertera di buku nikah. Yang mana di antara poinnya ialah: “Apabila saya: ... (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ... dan karena perbuatan tersebut istri saya tidak rida atau tidak rela dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan, kemudian istri saya membayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”
Dari shighat ta’liq talak poin 2 tersebut di atas, maka di Indonesia, batasan maksimal seorang suami tidak memberikan nafkah batin ialah 3 bulan. Meski demikian, talak tidak serta merta jatuh (terjadi) karena hal itu masih tergantung pada kerelaan istri. Apabila istri rela, maka pernikahan masih bisa berjalan, sementara jika istri tidak rela, maka si istri boleh mengajukan gugat cerai di pengadilan. Wallahu a’lamu.