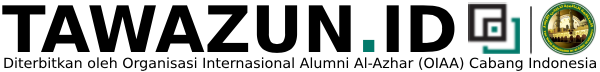“Manusia pada umumnya terbagi menjadi empat golongan. (Pertama) ia yang berilmu dan sadar bahwa dirinya berilmu, ialah orang alim, maka ikutilah ia. (Kedua) ia yang berilmu namun tidak sadar bahwa dirinya berilmu, ialah orang yang terlelap, bangunkan ia. (Ketiga) ia yang bodoh dan sadar bahwa dirinya bodoh, ialah orang yang butuh bimbingan, bimbinglah ia. (Keempat) ia yang bodoh namun tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ialah si bebal, tolak dan jauhilah ia.” Al-Khalīl bin Ahmad.[1]
Menurut saya, klasifikasi ini terasa begitu relevan akhir-akhir ini, terutama golongan terakhir; ia yang bodoh dan tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Yang lebih mencengangkan, kepandirannya tidak berhenti sampai di sini, alih-alih diam mereka justru berhalusinasi dan terperangkap dalam ilusi “merasa tahu” dan “merasa wajib memberi tahu”. Di era yang serba terbuka seperti sekarang, kita bakal mudah menemui “pakar-pakar” dadakan, tidak hanya pada bidang keilmuan tertentu, bahkan dalam semua bidang keilmuan. Salah satu yang terdampak fenomena ini ialah bidang ilmu keagamaan, dalam hal ini Islam.
Betapa banyak “ulama” yang bermunculan akhir-akhir ini yang bahkan kapabilitasnya pun sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan namun ia begitu banyak diamini oleh para pengikut setianya. Betapa banyak orang yang mendaku sebagai “ulama” lalu ia merasa berhak untuk menjustifikasi sana-sini. Tebar fatwa ini-itu juga memberi stigma dan menghukumi sesuai apa yang ia inginkan. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan retoris cukup baik lalu secara persuasif menghimpun banyak pengikut tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya.

Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan; rasional dan logis. Ia bukan semata-mata hadir sebagai dogma yang dilayangkan secara serampangan. Islam begitu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan segala konsekuensi yang mengikutinya, termasuk kepakaran. Hak maupun kewajiban diikuti dan mengikuti seputar kepakarannya. Gampangnya, kenyataan ini mempunyai dua konsekuensi logis: hak berbicara dan menyampaikan atas suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu adalah pakarnya, juga kewajiban siapapun yang merasa tidak memiliki kepakaran atas suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengikuti pakarnya.
Tuhan secara tegas telah berfirman, “Maka bertanyalah kalian sekalian pada ahli dzikr jika kalian sekalian tidak mengetahui.” Kata dzikr dalam ayat ini memang diinterpretasikan berbeda-beda oleh ahli tafsir, namun pemaknaannya terpusat pada satu benang merah: ia yang mempunyai ilmu pengetahuan.[2] Dari ayat ini pula, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak bertanya secara serampangan melainkan kepada pakarnya. Konsekuensi logis selanjutnya tentu saja tidak semua orang berhak berbicara—atas suatu masalah tertentu—kecuali ia benar-benar mengerti, memahami, dan menguasai permasalahan tersebut.
Masalahnya, meskipun kita sudah menjernihkan masalah sedemikian rupa, masih terdapat satu hal lagi yang menjadi bumerang: nafsu. Ya, nafsu untuk berbicara, nafsu untuk didengarkan dan tetek-bengeknya acap kali mengeruhkan air yang sebelumnya jernih. Pada titik ini, yang perlu dikontrol ialah nafsu itu sendiri, agar kiranya kita tidak berbicara atas suatu masalah yang berada di luar wilayah dan kapasitas kita. Alih-alih memberikan manfaat dan kemaslahatan, justru kesesatan yang didapat, dhalla wa adhalla: sesat-menyesatkan.
Dalam urusan agama, saleh ritual tidak cukup digunakan sebagai acuan seseorang layak berfatwa, sebagaimana halnya seseorang yang terbiasa hidup bersih dan sehat tidak cukup layak digunakan sebagai acuan untuk membicarakan serangan jantung! Li kulli maqām maqāl, wa li kulli maqāl maqām. Setiap perkataan ada tempat dan kedudukannya, juga setiap tempat dan kedudukan ada perkataannya (yang sesuai).

Dalam ilmu tafsir misalnya, seseorang berhak menafsiri Alquran setelah setidaknya menjadi pakar dalam belasan ilmu lain, seperti gramatika bahasa meliputi nahwu (sintaksis), sharf(morfologi), paramasastra (baik ma’āniy, bayān maupun badī’) dan isytiqāq; fikih, usul fikih, ilmu-ilmu Alquran termasuk ilmu rasm (penulisan), ilmu-ilmu hadis dan lain sebagainya. Tanpa kepakaran belasan cabang ilmu ini, seseorang tidak dianggap layak menjadi seorangmufassir. Begitu pula ilmu-ilmu agama yang lain, masing-masing saling terintegrasi. Lalu, bukankah menjadi aneh ketika seseorang yang bahkan tidak hafal Alquran dengan angkuhnya berlagak menginterpretasi ayat Tuhan? Lalu, bukankah menjadi aneh ketika seseorang yang bahkan tidak menguasai dirāyah hadis berbicara tentang sahih-lemahnya sebuah hadis?
Pada akhirnya, mari kita bermain analogi sederhana. Seseorang lulusan sekolah dasar berperan seolah-olah menjadi dokter hebat dengan segala retorikanya. Kemudian seseorang yang baru beranjak peduli dengan kesehatannya mulai terbuai oleh retorika sang dokter abal-abal dengan mengamini dan mengimani segala apa yang diucapnya. Lalu, apa yang bakal terjadi? Anda sangat bisa menebaknya.[]
Catatan kaki:
[1] Ungkapan atas klasifikasi ini dinisbatkan kepada beberapa orang, di antaranya Sayyidina Ali -Karrama Allahu Wajhah. Namun, dalam hal ini penulis mengutip Imam al-Ghazali dalam bukunya Ihyā ‘Ulūm ad-Dīn. Lebih lanjut, lihat Abū Hāmid al-Ghazāliy, Ihyā ‘Ulūm ad-Dīn (Berirut: Dār al-Ma’rifah, 1982), hlm. 59.
[2] QS. An-Nahl, ayat 43. Bisa merujuk berbagai literatur tafsir semacam Mafātīh al-Ghaib karya ar-Rāzi dan lain sebagainya.