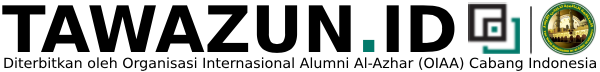Era medsos menampakkan fakta yang menarik, bahwa tiap orang memiliki kebebasan sekaligus kesempatan untuk mengomentari segala isu yang berkembang di dunia, mulai dari urusan yang remeh-temeh hingga paling besar sekalipun. Nahasnya ketika tidak diimbangi dengan kemampuan menahan diri yang baik, akhirnya yang muncul adalah budaya menyebar hoaks, saling olok-mengolok, fitnah, dan berbicara pada hal-hal yang bukan ranah kemampuannya.
Dalam kasus vaksin Covid-19 misalnya, dilansir dari liputan6.com, bahwa menurut Kominfo hingga hari Minggu (29/5/2022) sudah tercatat temuan 505 hoaks yang tersebar di berbagai media sosial dan sebarannya mencapai hingga 2.718 konten. Sebaran paling banyak berita tersebut ditemukan di Facebook, yakni 2.718 konten hoaks seputar vaksin Covid-19.

Oleh karenanya, kemampuan menahan diri, khususnya untuk diam, sangat diperlukan di era medsos ini. Ketika tiap orang memiliki seni untuk diam ini, saya rasa tidak akan ada orang yang berani secara serampangan berkomentar terhadap bidang yang bukan keahliannya. Budaya menyebar hoaks pun dengan sendirinya akan hilang apabila para pengguna medsos tidak terburu-buru share-like atau “diam” sebelum benar-benar klarifikasi dan mencari kebenaran.
Dalam bermedsos, seni untuk diam dibangun atas tiga proses: memahami, menghayati, dan mengekspresikan. Ketiga proses ini diadopsi dari konsep hermeneutika Wilhelm Ludwig Dilthey (1833-1911), seorang ahli hermeneutika sejarah dari Jerman.
Menurut Dilthey, ketika seseorang ingin memahami teks (yang dalam hal ini adalah ‘konten-konten medsos’) mesti masuk dalam lingkaran hermeneutik: pemahaman (Versthen), kemudian penghayatan (Erlebnis), lalu ekspresi atau ungkapan (Ausdruck).
Dalam hal ini, setiap konten yang kita baca atau berita yang kita terima mesti terlebih dahulu melalui proses ‘memahami’ (Verstehen), yaitu dengan melalui dua tahapan: pertama, tahap “empati”, dengan mencoba menyusuri kembali kronologi dan situasi yang melatarbelakangi munculnya “teks”: bagaimana berita itu bisa muncul? Kedua, tahap menemukan “Roh Objektif” atau konteks di mana “teks” itu hadir, baik dari segi adat istiadat, kultur zaman, gaya hidup, situasi politik, dll: apa yang memengaruhi munculnya berita itu?
Setelah proses memahami, dilanjutkan dengan proses “menghayati” (Erlebnis) konten-konten berita, yaitu proses ‘masuk ke dalam’ peristiwa secara langsung, tanpa jarak, seakan-akan pembaca mengalami sendiri peristiwa dalam berita atau konten tersebut.

Setelah ‘memahami’ dan ‘menghayati’, pembaca ‘mengungkapkan’ (Ausdruck) hasilnya ke dalam ide, sikap atau tindakan tertentu: bagaimana saya harus bertindak atau bersikap?
Apabila diandaikan bahwa medsos –dengan segala seluk beluknya– adalah realitas “teks” sedangkan hoaks, nafsu berkomentar serampangan, dan borok sejenisnya adalah penyakitnya, maka seorang pengguna medsos (atau pembaca) perlu membekali diri dengan seni untuk diam –dengan asumsi bahwa berkomentar, share, dan nge-like adalah bagian dari berbicara.
Sehingga ketika ia mendapatkan broadcast tentang isu tertentu, menjumpai debat kusir di FB atau sejenisnya, mendapati status hoaks, atau menemukan problem yang bukan ranah keahliannya, tidak serta merta ikut share-like, mengomentari ataupun menangapi, sebelum benar-benar mengembalikannya kepada kaidah seni untuk diam.
Dengan kesadaran ini, dunia medsos akan sehat kembali, karena dipenuhi oleh orang-orang yang berpikiran jernih, sama sekali diam dan tidak “berbicara” sebelum memahami (Verstehen) baik pembawa berita maupun konteks umumnya, menghayati (Erlebnis) dengan mencoba merasakan langsung problem yang hadir, dan kemudian baru mengekspresikan (Austruck) –baik dengan tindakan “diam” atau komentar.
Dalam literatur Islam, anjuran untuk diam ini ternyata sudah sejak lama digaungkan oleh para Nabi, ulama dan bijak bestari. Misalnya, Imam Jalaluddin As-Suyuthi (w: 911 H), ulama produktif yang hidup di abad ke-15 H di Kairo, Mesir, suatu waktu pernah merangkum satu bab dari kitab karangan Imam Abu Bakr Muhammad Ibnu Abi Dunya (w: 281 H) yang berjudul “Kitab Ash-Shamti wa Adab Al-Lisan” (Kitab tentang Diam dan Etika Berbicara). Selanjutnya oleh As-Suyuthi kitab rangkuman itu ia beri tajuk “Husni Ash-Shamti fi Ash-Shamti”. Di dalamnya As-Suyuthi memaparkan 115 riwayat, terdiri dari hadits Nabi, kalam ulama dan para bijak bestari mengenai keutamaan sikap diam dan menjaga lisan, yang salah satunya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh sabahat Abdullah bin Umar: “Man shamata, naja” (siapa diam akan selamat).
Ketika melihat realitas dan problem zaman di mana Ibnu Abi Dunya dan As-Suyuthi hidup, kita akan dapati bahwa sangat logis ketika dua ulama besar ini kemudian mengangkat urgensitas diam dan menjaga lisan dalam tulisan mereka. Pasalnya Ibnu Abi Dunya hidup di masa di mana pergolakan politik dan pertikaian antar aliran keagamaan sedang merebak. Setiap paham kekeuh memegang kebenaran yang mereka yakini dan menyalahkan paham yang lain. Sehingga tren pertikaian, perseteruan pendapat, debat kusir, dan saling buruk sangka antar umat Islam menjadi makanan sehari-hari yang tak terelakkan.
Tak jauh berbeda dengan zaman As-Suyuthi. Ia hidup di mana Mesir saat itu belum lama menjadi pusat pemerintahan Islam, setelah Al-'Abbasiyah di Baghdad kalah oleh tentara Mongol. Persoalan utama yang muncul adalah mengenai ideologi pemerintahan yang mesti diterapkan saat itu. Persaingan, perdebatan, dan pertikaian dalam merebutkan dominasi ideologi negara antar pemimpin Dinasti Al-Mamalik mencuat ke permukaan. Sehingga dibangun masjid, sekolah, madrasah-madrasah dengan tendensi ideologis tertentu yang pro pemerintah, para ulama diundang ke istana untuk berdebat dan mempertahankan argumentasi mereka.
Berangkat dari problem itulah kemudian baik Ibnu Abi Dunya maupun As-Suyuthi mengangkat urgensitas diam dan menjaga lisan sebagai counter dan solusi atas realitas dan konteks zaman mereka. Seakan mereka ingin menegaskan bahwa diam, menjaga lisan dari berkomentar tidak produktif dan nir-manfaat, tidak sembrono mengutarakan pendapat, dan menghindari debat kusir adalah salah satu sunah Nabi dan jalan para bijak bestari. Sedangkan menyebar hoaks adalah lawan dari kebijaksanaan itu sendiri.

Akhirnya, apabila era medsos adalah era dengan kecenderungan berkomentar dan unjuk diri, maka seni untuk diam menemukan kembali konteks dan urgensitasnya. Diam dan menjaga lisan sebagai jalan para bijak bestari yang sangat ditekankan dalam Islam, di era ini bisa diimbangi dengan proses memahami-menghayati-mengungkapkan ketika menyaring setiap berita atau konten yang ada, utamanya untuk meng-counter penyebaran hoaks dan bicara serampangan di medsos.
Sehingga tak salah apabila Imam Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumiddin-nya memuji sikap diam dan menyebutkan bahwa ada 20 penyakit yang berkenaan dengan mulut (āfat al-lisan) manusia.