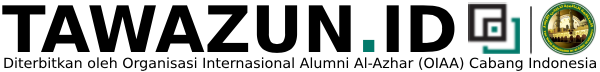Sejak akhir abad ke-20, antroposentrisme dipandang sebagai biang keladi dari porak-porandanya lingkungan hidup, sehingga dibutuhkan suatu cara berpikir baru yang dapat mengatasi segala kerusakan itu. Para pemikir lingkungan seperti Arne Naess sampai sejarawan Arnold Tonybee berusaha meringkus hantu antroposentrisme ini dalam segala lini, yang meletakkan manusia sebagai pusat dari alam semesta.
Akibat dari cara pandang antroposentris ini adalah memungkinkan penguasaan manusia atas alam demi kepentingannya semata, menyebabkan krisis lingkungan yang terjadi seperti saat ini tak dapat dihindari. Karena itu, tawaran yang dimunculkan dari permasalahan ini, sebagai jalan keluar dari cara berpikir antroposentris, adalah ekosentrisme, sebagai kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme.

Ekosentrisme, secara sederhana, merupakan suatu etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang-hidup (biotik) dan tak-hidup (abiotik). Seluruh komunitas ekologis itu saling terkait satu sama lain, dalam arti, sama-sama bernilai. Misalnya, manusia sama bernilainya dengan hewan dan tumbuhan, dan manusia, hewan, serta tumbuhan (biotik) itu sama bernilainya dengan batu, cahaya, atau partikel (abiotik). Artinya, tak ada batasan nilai antara yang-hidup dan tak-hidup itu.
Dalam hal ini, haruslah disadari, bahwa ekosentrisme memiliki keterbatasannya sendiri. Selain mengesampingkan nilai-nilai manusia dan cenderung menyakralkan alam, ekosentrisme pun tak pernah benar-benar terbebas dari bayang-bayang antroposentrisme. Ia masih menghendaki pemulihan alam yang kadung rusak ini untuk keberlangsungan hidup manusia kedepannya, alih-alih ingin meletakan semua makhluk—yang-hidup dan tak-hidup—dalam posisi yang setara.
Menurut Neil Smith, dalam bukunya Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space (2008), setiap rumusan, setiap narasi yang dibangun tentang alam akan selalu berwatak antroposentris, sekeras apapun usaha kita mengambil jarak terhadap persepsi manusia dalam memahami dan menjelaskan alam. Sebab, pada kenyataannya, manusia selalu berada di dalam alam, menjadi bagian dari alam itu sendiri. Dengan demikian, menjadi jelas adanya apabila ekosentrisme dengan segala keterbatasannya itu tak benar-benar bisa terbebas dari bayang-bayang antroposentrisme, sejauh alam atau lingkungan hidup itu sendiri dialami dan dihidupi oleh manusia sebagai subjek antroposentris. Begitu pula dengan Islam, yang seringkali dipandang sangat antroposentris.
Islam memang tak dapat sepenuhnya bisa melepaskan diri dari jerat antroposentrisme, bahkan harus saya katakan di sini, bahwa ia tak selamanya anti-antroposentrisme. Hal ini tak perlu diratapi secara berlebihan, karena Islam memang memiliki konsep tersendiri tentang manusia dan hubungannya dengan alam.
Beberapa ayat Al-Quran seperti Surah Al-Baqarah ayat 29, Surah At-Tin ayat 4, dan Surah Al-Baqarah ayat 30, menjelaskan secara gamblang perihal esensi manusia, sebagai makhluk yang istimewa, makhluk berakal, serta memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya, dengan syarat, tidak melampaui batas dan melakukan kerusakan. Ayat-ayat inilah yang selalu dianggap sangat antroposentris.
Anggapan itu memang tak sepenuhnya keliru, meski tetap tak cukup memadai untuk menjustifikasi Islam sebagai agama antroposentris sepenuhnya. Kekeliruan menganggap Islam sebagai agama antroposentris sepenuhnya memang seringkali terjadi akibat pemahaman atas Al-Quran yang parsial, atau tidak secara menyeluruh. Padahal, jika mau melihat lebih jauh lagi, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk tidak melampaui batas dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi (lihat surat Al-Araf: 46), dan memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi (lihat surat Hud: 61). Maka tuduhan kepada Islam sebagai agama antroposentris par excellence sangatlah rapuh.
Walaupun demikian, menurut saya, umat Islam harus berani untuk menyatakan bahwa agamanya memang memiliki kecenderungan yang antroposentris sekaligus ekosentris. Tetapi, bukan antroposentrisme ala Francis Bacon yang menekankan pada penguasaan atas alam, entah atas nama pembangunan atau profit semata (meminjam istilah Vandana Shiva, sebagai antroposentris kapitalis). Bukan pula ekosentrisme romantik yang menguduskan alam, sebagai suatu wujud yang sudah baik dengan sendirinya.
Dalam hal ini, umat Islam harus membangun pemahamannya sendiri agar tidak larut dalam pembedaan dari kedua gagasan yang saling berlawanan itu, yang pada akhirnya, sangatlah tidak tepat dan tidak menguntungkan bagi umat Islam sendiri. Alasannya, karena akan menyeret umat Islam pada ekstrim tertentu: menyepakati antroposentrisme atau ekosentrisme secara total.

Umat Islam harus mampu menciptakan suatu rumusan atau konsep yang mendasarkan dirinya pada interaksi yang seimbang antara manusia dan alam, bersifat inter-relasi antara manusia dan alam. Dengan sikap seperti ini, hubungan manusia dengan alam tidak lagi berwatak satu arah saja di mana manusia sepenuhnya berkuasa atau tunduk kepada alam, tetapi saling mempengaruhi.
Manusia dan alam memiliki kapasitas yang sama untuk saling mempengaruhi satu sama lain, dan untuk saling menghidupi dengan batas-batasnya sendiri. Sebab Allah memang menciptakan manusia untuk mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi, dan terutama untuk memakmurkan bumi. Istilah khalifah ini memang seringkali dipahami secara antroposentris, bukan dimaknai secara dialektis. Ada salah satu tafsir yang sangat berguna untuk memahami konsep khalifah ini.
Dalam Jam’i Al-Bayan fi At-Ta’wil, Imam Ath-Thabari memaparkan dengan sangat baik pada istilah khalifah ini. Khalifah diartikan sebagai penduduk dan pemakmur bumi untuk menggantikan peran iblis yang telah tinggal lebih dulu di bumi, tetapi mereka telah melakukan kerusakan atasnya. Allah pun menciptakan manusia sebagai khalifah untuk menggantikan iblis yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, hingga dimusnahkan oleh para malaikat. Karena itu, secara bahasa, khalifah bisa dimaknai sebagai makhluk yang datang kemudian dan menggantikan makhluk sebelumnya untuk memakmurkan bumi, bukan malah sebaliknya.
Sehingga persoalannya bukan lagi terletak pada padangan Islam tentang konsep manusia dan hubungannya dengan alam seperti dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang cenderung ditafsirkan dengan sangat antroposentris atau ekosentris. Akan tetapi, lebih kepada siapa yang merusak alam ini secara membabi-buta, atau manusia seperti apa yang membuat dunia ini hancur lebur, apa motif di baliknya, dan bagaimana mekanismenya.

Menjadi hal konyol apabila kerusakan alam ini dibebankan kepada seluruh umat manusia, meskipun, kenyataannya, tidak semua manusia memiliki kendali sepenuhnya atas kenyataan atau alam. Misalnya, para petani Kendeng dan Kulon Progo yang ruang hidupnya dirampas oleh para pemodal rakus dengan alasan pembangunan infrastruktur dan profit semata. Lantas apakah, dalam hal ini, para petani Kendeng dan warga Kulon Progo itu masuk dalam antroposentrisme, yang selama ini dipandang bertanggung jawab atas terjadinya krisis lingkungan? Bagi saya, sangat jelas, mereka bukan bagian dari antropos yang merusak itu!
Artinya, tak semua manusia bisa diringkus dalam jaring-jaring antroposentrisme (kapitalis). Karena tak semua manusia memiliki kendali, tak semua manusia memiliki andil yang sama atas kenyataan atau lingkungan hidup, terutama di bawah sistem kapitalisme. Hanya dalam sistem kapitalisme-lah alam dipandang sebagai “budak” untuk memuaskan nafsu serakah para orang-orang rakus (baca: kapitalis). Al-Quran telah memberi tahu kita dengan sangat gamblang bahwa terdapat orang-orang yang selalu membuat kerusakan, alih-alih dengan melakukan perbaikan (lihat Surah Al-Baqarah: 11, dan Surah Al-Maidah: 32).
Maka umat Islam harus dengan tegas menolak sistem kapitalisme yang sangat merusak itu, serta harus memiliki formula yang jitu dan tepat sasaran, yang selalu menekankan pada maslahat bersama dan mencegah kerusakan yang lebih besar (dar' al-mafasid), tanpa harus terombang-ambing antara menjadi antroposentrisme atau ekosentrisme secara ekstrim. Hanya dengan menolak dan mengubah kapitalisme, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan benar-benar terwujud. Wallahu a’lam.