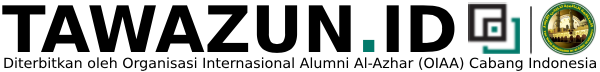Ada satu doa yang bagi saya penting untuk menyambut serta merefleksikan Ramadan esok hari. Doa tersebut berbunyi, “Allahumma Sallimni min Ramadhan, wa sallim Ramadhana Li, wa tasallamhu minni Mutaqabbilan” yang artinya, “ya Allah selamatkanlah aku dari (rahmat dan laknat) bulan Ramadan, juga selamatkanlah Ramadan dari (perbuatan-perbuatan keji) aku. Serta terimalah amal-amalku selama bulan Ramadan”. Doa ini menurut saya sangat esensial—sebagaimana dawuh Habib Novel dalam salah satu ceramahnya, bahwa bisa jadi Ramadan, selain membawa rahmat, ia juga membawa laknat bagi perbuatan-perbuatan keji nan dosa. Kemudian doa agar kesucian Ramadan tidak menjadi ternodai akibat kemaksiatan kita. Artinya kita memohon keselamatan dari dua-duanya: laknat Ramadan serta kemaksiatan kita di bulan suci tersebut.
Doa tersebut membuat saya merenung sejenak sambil sedikit khawatir: jangan-jangan kita tidak sanggup bahkan tidak akan bisa ideal dalam menyambut bulan yang suci dan mulia itu. Dalam bahasa sufi, jangan-jangan kita masih terhijab untuk melihat hakikat Ramadan. Ada batas dan jarak yang membuat kita tak sanggup menjangkaunya. Sebabnya, mungkin selama ini kita hanya memahami Ramadan dengan bayangan zahir saja: bulan, musim, takjil, dan sahur. Padahal ia bukanlah wujud material sehingga Ramadan masih asing dan tidak ada dalam kesadaran kita. Itulah mungkin hijab yang menjadi ‘jarak’ antara kita dengan bulan suci tersebut.
Barangkali itulah menurut saya makna ‘keselamatan’ dalam doa di atas. Kesiapan kita untuk menyambut Ramadan tergantung pada seberapa jauh kita selamat dari hijab-hijab antara kita dengannya. Sebab dari tahun ke tahun, mungkin Ramadan hanya kita pahami sebagai rutinitas ritual tahunan belaka. Segala sesuatu yang hanya dilalui sebagai rutinitas, ia akan kehilangan makna. Ramadan lebih dari itu, ia adalah kesadaran kita. Selama kesadaran kita belum utuh dan total, Ramadan akan hilang dari subjek diri kita lalu hanya menjadi simbol-simbol religius dalam gegap-gempita dunia nyata maupun media sosial.
Hal ini senada dengan penjelasan Syekh Muhammad Mushthafa Al-Maraghi dalam Majalah Al-Azhar edisi Ramadan pada tahun 2017 yang bertajuk “Ramadan fi Turats Majallatil Azhar. Menurutnya, alasan Allah menurunkan Ramadan tiap tahunnya, sebagai momentum paling mulia, adalah berkat ibadah puasa. Menurut beliau, hikmah terbesar puasa adalah untuk mempersiapkan keridaan dan ketenangan jiwa manusia agar sanggup menerima curahan (Fuyudhat) dari Al-Haqq. Sebab hakikat puasa adalah obat spiritual bagi manusia. Oleh sebab itu, puasa adalah pembebasan jiwa dari syahwat zahir: seperti makan, minum, dan hubungan seksual kemudian syahwat batin: kebencian, kedengkian, hingga balas dendam. Dengan pembebasan itu, spiritualitas manusia akan sanggup naik menuju langit ruh, akhirnya bisa menerima curahan dan madad dari Allah SWT secara langsung.
Makna di atas kemudian dikuatkan dengan kehadiran puasa sebagai ibadah privat (Ibadah Sirriyah) antara Allah dan hamba-Nya yang spesial. Sebagaimana dalam Hadits Qudsi, “Fainnahu Li wa ana Ajzi bihi”. Berbeda dengan ibadah lainnya, tidak ada kemudian orang yang bisa mengukur keikhlasan ibadah puasa ini kecuali Allah saja. Karena itu, Ramadan juga disebut dengan bulan kesabaran sebagaimana puasa itu adalah separuh dari kesabaran (Nishfun min Ash-Shabr). Orang-orang yang disifati oleh Al-Quran mendapat balasan tanpa perhitungan, “Innama yuwaffa ash-shabirun ajrahum bighairi hisab”. Pada intinya, Syekh Muhammad Mushthafa Al-Maraghi menekankan puasa sebagai bentuk totalitas ‘menahan diri’ dalam rangka membebaskan jiwa dari segala hal yang menghalangi (Menghijab) diri dari Allah SWT.
Puasa yang Ideal
Tak heran kemudian dalam kitab aforisme Hikam-nya yang monumental, Ibnu Athaillah berkata“Kaifa yutashawwaru an-yuhjibahu syaiun wahuwalladzi Zhahara fi kulli syaiin”, yang berarti, “Bagaimana mungkin dipahami ada sesuatu yang bisa menghijab (menghalangi) dirinya (dari manusia), sedang Ia adalah dzat yang tampak di dalam segala sesuatu”. (hikmah ke 18). Kalimat di atas merupakan salah satu dari sembilan untaian hikmah yang esensinya menjelaskan mustahilnya Allah itu terhijab dari manusia. Sampai-sampai diulang-ulang dengan redaksi dan penekanan yang berbeda-beda: Azh-hara, Zhahara bi, Azh-Zhahir likulli, Azh-Zhahir qabla kulli, Azh-haru min kulli, al-wahid all-ladzi laisa ma’ahu, aqrabu ilaika, laulahu ma kana wujud. Artinya hijab (terhalangnya) manusia dengan Tuhan, itu sejatinya datang dari manusia. Bukan dari Tuhan. Imanensi manusia yang terpenjara dalam syahwat-materiil membuat entitasnya semakin jauh untuk menjangkau entitas Tuhan yang transenden.
Jika direfleksikan dalam situasi bulan Ramadan ini kemudian: artinya Ramadan hadir berikut ibadah puasa, untuk mengikis hijab yang ada dalam diri kita: mengangkat dan meninggikan kualitas manusia: membebaskannya dari belenggu syahwat. Dengan demikian, Ramadan adalah kesempatan besar untuk semakin dekat dan intim berinteraksi dengan-Nya sampai kemudian luruh, hilang hijab yang selama ini membatasi diri kita dengan-Nya sang Maha Absolut. Subhanahu wa ta’ala.
Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana bentuk puasa yang ideal? Puasa yang sanggup membebaskan sekaligus mendatangkan perubahan radikal dalam diri kita? Merujuk pada penjelasan Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam dalam Ihya’ Ulumiddin; kategori puasa yang masih menjebak dan menyisakan hijab antara kita dengan Allah SWT, adalah puasa yang dipahami sebagai rutinitas sahaja. Beliau menyebutnya dengan puasanya orang awam (shaum al-umum):mereka adalah orang yang dalam berpuasa tak lebih dari meninggalkan makan dan minum saja. Dengan redaksi lain, mereka yang selama Ramadan hanya terjebak pada rutinitas mengubah pola makan dan minum saja. Maka, mereka masih terhijab dari hakikat bulan Ramadan yang sejatinya dapat mengantarkannya lebih dekat dengan Allah SWT.
Sedangkan puasa yang ideal adalah puasanya orang khusus (shaum al-khusus), bahkan kalau bisa puasanya para Nabi dan Wali (shaum khushusi al-khusus). Puasanya orang khusus adalah puasa dalam makna totalitas mencegah anggota badannya untuk melakukan kemaksiatan. Ada enam tindakan setidaknya menurut Imam Al-Ghazali: menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran dan seluruh anggotan badan lainnya: mempersedikit berbuka dengan yang halal, menggantungkan hati antara rasa harap (raja’) dan cemas (khauf) apakah ibadahnya diterima atau tidak.
※ Hal Ihwal Terkait Penyambutan Ramadan
Sedang puasanya para Nabi dan wali Allah bermakna totalitas menahan diri (hati) dari segenap keinginan-keinginan hina dan pemikiran duniawi. Dalam bahasa lain: berpuasa dari segala sesuatu selain Allah. Sampai Imam Al-Ghazali mengutip sebuah maqalah: “Barangsiapa yang dalam dirinya tergerak, saat siang hari, untuk berusaha (karena kurang tawakkal) mencari bekal berbuka nantinya... maka gerak itu dianggap sebuah dosa yang membatalkan puasanya.” Inilah puasa yang dapat membebaskan dan membuka ‘hijab’ antara kita dengan Allah SWT. Merekalah definisi orang-orang yang benar-benar memahami, menyatu dengan Ramadan baik dalam pikiran, hati dan lakunya. Merekalah orang yang ‘selamat’ dan benar-benar siap menyambut Ramadan esok.
Alhasil, bagi kita yang masih berat dan senantiasa pada level ‘awam’ untuk mendekati Ramadan, paling tidak jangan sampai kita menodai dan memperburuk kondisi itu dengan laku-laku kemaksiatan. Terutama kemaksiatan sosial yang kasat mata: zalim pada orang lain, dengki, dan sebagainya. Allahumma sallim ramadhana li, Amin.